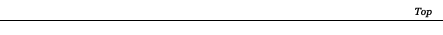Country-bution 2.0 *, Tentang Keterlibatan & Posisi Seni Rupa dalam Masyarakat Sekarang
February 15, 2011

Farah Wardani, Direktur Eksekutif Indonesia Visual Art Archive, Yogyakarta, Indonesia
Isu tentang keterlibatan seniman dalam perkembangan masyarakat ini sebenarnya sudah pernah dieksplorasi oleh Hendro Wiyanto 8 tahun lalu di Biennale Yogyakarta 2003, dengan tajuk ‘Country-bution’, yang salah satunya mempersoalkan kontribusi seniman pada ruang sosialnya dan negara. Namun, dulu konteksnya sesuai dengan situasi saat itu, mencoba menawarkan berbagai strategi visual seniman-seniman Yogya dari perspektif perkembangan komunitas/kolektivitas/ruang alternatif dalam seni rupa, yang saat itu sejalan dengan semangat pasca-reformasi.13 tahun sudah berlalu sejak reformasi negeri ini, dan telah banyak terjadi serta tercipta di dunia. Saat ini, isu pusat/marjinal tidak lagi mendominasi dalam dinamika dan kajian seni-budaya, dan infrastruktur seni telah menjadi lebih kompleks. Pasar seni rupa, di satu sisi, menawarkan sebuah ‘idealisasi’ berkesenian sebagai profesi yang memiliki nilai kapital yang tinggi, yang seringkali ‘dituduh’ sebagai penyebab utama pengkaryaan seni visual secara umum menjadi semakin ‘apolitis’.
Namun, disini kita tidak sedang membahas soal itu. Bila dilihat di sisi lain, ada pertanyaan lebih besar. Seniman dan praktek seni visual sekarang ini bekerja dalam ruang sosial dan politik yang juga lebih kompleks dibandingkan dahulu. Saat ini, ruang yang ditawarkan di NKRI tercinta ini adalah sebuah ruang berantakan dalam situasi ‘democrazy’, dengan eforia media dan internet, chaos kebebasan berekspresi/berpendapat versus berbagai upaya represi dan kekerasan dari ‘musuh-musuh’ yang beragam dan tidak jelas.
Sekarang, setiap orang bisa melontarkan sumpah-serapah kepada apa dan siapa pun, untuk kemudian diserang lagi oleh siapa pun, dan kita tinggal menunggu konflik, skandal, eforia, polemik atau subversi apa saja yang akan datang esok hari, untuk kemudian berganti lagi pekan depan. Dan apakah semua riuh-rendah suara itu memberi solusi? Seperti yang kita rasakan sendiri sampai sejauh ini, tidak. Sementara, konflik horizontal mengancam untuk hadir secara nyata dengan berbagai letupan kekerasan dan bentrokan antar perbedaan kelompok dan golongan disana-sini.
Bagaimana seni visual bisa terlibat dan berbicara lebih lantang dalam situasi seperti ini? Apakah bisa? Ataukah memang ia, akhirnya, seperti yang banyak diutarakan (kalau tidak bisa dibilang pembenaran) oleh pelaku seni, ‘hanya mengisi celah/kekosongan’, ‘menawarkan alternatif lain’, dan sebagainya. Apakah benar cukup sampai disitu, tidak lebih? Kalau memang benar ia cukup diterima sebagai sebuah ‘dimensi’ tersendiri yang mewakili ruang kecil (niche) kelas menengahnya sendiri, sejauh mana ia berperan dan berkembang? Apakah posisi itu pun sudah jelas?
Dan kalau misalkan sebaliknya, bahwa masih ada kepercayaan akan peran/posisi seni yang (bisa) besar, dengan tanggung jawab sosial yang besar, dan melontarkan hal-hal yang besar serta terlibat lebih mendalam dalam situasi yang riuh-rendah seperti sekarang, seperti apa dan sekali lagi, sejauh mana?
Keterlibatan yang saya maksud disini adalah dalam hal estetika dan pengkaryaan, bukan dalam hal keterlibatan seniman/pekerja seni secara infrastruktural seperti turut melakukan advokasi ke pemerintah/negara dan sebagainya. Memang, itu sudah banyak diupayakan dengan hasil yang belum maksimal, tapi kemudian juga masih ada pertanyaan, bagaimana dengan karya/praktek seninya itu sendiri? Apakah kita masih bisa berharap kepada sebuah objek seni visual, atau sebuah pameran, atau sebuah gerakan kesenian, misalnya, bahwa ia dapat berbicara dengan tajam tentang persoalan publik, kepada publik, tanpa terpeleset menjadi sekadar perayaan atau curahan reaksioner semata yang kemudian lewat begitu saja?
Biennale Yogyakarta X tahun 2009 telah sedikit banyak menyinggung persoalan ini, dengan ‘melimpahi’ setiap sudut ruang publik kota dengan karya seni, dan dengan tawaran semangat ‘gugur gunung’ dimana begitu banyak seniman ikut serta, dengan karya yang ‘bersentuhan’ dengan banyak orang, dan cukup lantang dalam menunjukkan kepada publik akan Yogyakarta sebagai ‘kota dengan populasi seniman terbanyak’. Namun sejauh pengalaman dan pengamatan saya, tawaran itu kemudian memang berhenti dalam tataran perayaan dan eforia keriaan akhir tahun. Ini hampir sama saja dengan eforia media itu sendiri, begitu banyak suara sampai tak menyisakan ruang refleksi yang cukup. Seperti halnya media massa saat ini, keterlibatan dan posisi seni rupa dalam masyarakat seolah tak bisa menawarkan hal lain selain dua hal: antara selebrasi atau reaksioner.
Intinya adalah bukan pada harapan bahwa seni visual dapat menjawab persoalan-persoalan publik tersebut, namun pada urgensi untuk menemukan strategi visual yang dengan tepat menggambarkan keterlibatan dan posisi seni rupa dalam keadaan urgensi saat ini, yang semakin hari semakin mengusik semua lapisan masyarakat untuk tak bisa tinggal diam. Apakah Biennale Yogya XI bisa menjadi kesempatan untuk mencoba menemukan strategi tersebut dan membuat pernyataan terhadap persoalan ini? (Farah Wardani, Direktur Eksekutif Indonesia Visual Art Archive, Yogyakarta, Indonesia)
*Judul artikel ini hanya ‘bermain’ dengan kata ‘Country-bution’, yang menjadi judul Biennale Yogyakarta 2003, rekaan kuratornya saat itu, Hendro Wiyanto. Bisa juga disikapi sebagai tribut untuk peristiwa tersebut. Ini juga bukan tawaran judul Biennale Yogya 11, hanya untuk tulisan ini saja.