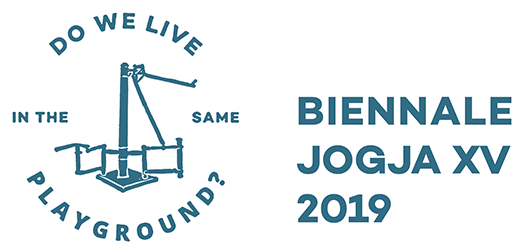Kepentingan Persoalan Pinggiran
Pinggiran di dalam Biennale Jogja juga tidak hanya membicarakan tentang isu-isu yang melingkupinya, tetapi juga membicarakan bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara berbagi permasalahan yang sama. Dengan kata lain, pinggiran adalah jembatan penghubungnya. Biennale Jogja berupaya menghubungkan berbagai wilayah yang mempunyai kompleksitas persoalannya sendiri-sendiri: Jogja, Aceh, Pontianak, Polman, Sabah, Pattani, Mindanao, Suluh, Ho Chi Minh, dll.
Selain berbagi persoalan bersama, dengan isu pinggiran, kita juga hendak melihat beberapa soal umum. Pertama, bagaimana subjek-subjek pinggiran membayangkan kawasan (Asia Tenggara) dan dunia global. Istilah “Asia Tenggara” bukanlah istilah generik yang lahir dari basis kesadaran masyarakat di kawasan ini. Asia Tenggara, sebagai penyebutan kawasan, muncul sebagai tampias dari perang dingin.
Ada relasi-relasi tradisional yang pernah berlangsung di kawasan ini, jauh sebelum batas-batas teritori dari negara-negara di kawasan ini ditetapkan. Kita tidak bermaksud untuk meromantisir relasi-relasi tradisional itu, tetapi hendak melihat efek-efek setelah era kolonialisme dan munculnya batas antar-negara-bangsa. Kawasan-kawasan semacam Pattani dan Sulu, misalnya, yang tidak hanya menjadi kawasan “antara”, tetapi juga berusaha membedakan dirinya dengan negara-negara yang kini membawahinya. Dinamika tersebut dapat kita telisik dari ekspresi-ekspresi kebudayaan atau kesenian mereka.
Kedua, pinggiran sebagai salah satu sarana untuk memahami kondisi yang tengah kita hadapi saat ini, terutama perihal masyarakat yang terbelah karena hegemoni kekuasaan tertentu. Situasi tersebut banyak berlangsung saat ini, pembelahan masyarakat karena perbedaan preferensi politik atau perbedaan-perbedaan lainnya. Kadang kita gagal membaca situasi itu, sekonyong-konyong mengambil posisi yang kita anggap paling benar.
Di dalam masyarakat pinggiran, dinamika antara kelompok penindas dan yang ditindas selalu hadir. Satu kelompok tertindas menindas kelompok tertindas lainnya, melahirkan pusaran konflik yang tidak ada habisnya. Semacam kelompok yang merasa paling demokratis menuding suatu masyarakat tertentu sebagai kelompok fundamentalis, begitu juga sebaliknya. Atau antara kelompok kaos merah dan kaos kuning di Thailand. Polarisasi semacam ini hadir, tetapi luput dipahami sebagai bagian dari permainan kekuasaan.
Ketiga, bagaimana kita belajar dari perspektif pinggiran. Sebagai gambaran, kita bisa belajar dari bagaimana masyarakat adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam mempertahankan hak ulayatnya dari ekspansi PT LONSUM yang ditopang oleh negara. Perusahaan tersebut, sejak era kolonial, sedikit-demi sedikit mencaplok tanah ulayat masyarakat adat untuk dijadikan perkebunan karet.
Sejak beberapa tahun belakangan ini, mereka berupaya melakukan pendudukan, reclaiming, di atas lahan-lahan yang dirampas oleh PT LONSUM, kendati mesti berhadapan dengan aparat. Begitu juga dengan perjuangan petani-petani Kendeng yang tengah berupaya melawan PT Semen Indonesia yang hendak mengeksploitasi pegunungan Kendeng, dan secara langsung mengganggu kehidupan masyarakat setempat.
Kedua kasus tersebut bukan hanya perkara hajat dan ruang hidup masyarakat yang terganggu, namun juga menjadi ancaman atas cara hidup yang diyakini masyarakat setempat–adat Sedulur Sikep di Kendeng dan Tallasa’ Kamase-masea (hidup sesederhana mungkin) di Kajang. Keduanya mempunyai prinsip yang sama: manusia dan alam sebagai entitas yang tidak bisa dipisahkan. Sialnya prinsip hidup semacam itu, saat berhadapan dengan kekuatan ekspansif berdalih investasi atau pembangunan, acap kali dilabeli sebagai prinsip hidup yang anti-kemajuan.
Kepentingan-kepentingan dari Biennale Jogja untuk menyoroti isu pinggiran tersebut sekaligus menjawab persoalan kedua yang diajukan sebelumnya. Pinggiran perlu kita pahami bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga memahami situasi nyata yang diberlangsung di berbagai tempat.