“Gereja Katolik di Asia adalah gereja kaum miskin. Bukan berarti kami memusuhi orang kaya. Kami memihak orang miskin, karena orang miskin itu memang tidak mempunyai way out!”
“Wanita itu adalah manusia yang paling dijajah, paling menderita. Teorinya boleh lain, tapi faktual, wanita berada dalam posisi itu. Dan saya mempunyai naluri memihak yang dijajah.”
Kutipan itu bisa dibaca dalam ruang Pameran Utama Biennale Jogja XVI Equator #6 2021. Di lantai dua sisi barat Gedung Jogja National Museum (JNM) Yogyakarta, dua ruangan khusus yang didedikasikan untuk Yusuf Bilyarta Mangunwijaya yang akrab kita sebut dengan Romo Mangun, meskipun belum pernah bertemu dan berkenalan.
Ruang A berisi buku-buku, kliping, dan video wawancara, Ruang B berisi lebih banyak kutipan, karya arsitek, dan dua buku. Dua ruangan itu memang terasa berbeda dengan karya-karya seniman di ruang lain, tapi di lain sisi, terasa kebesaran Romo Mangun terlalu kecil ditampilkan dalam dua ruang itu. Ruangan yang akan terasa hampa jika melewatkan detail-detail arsip yang ditampilkan. Sedikit saran saja, Anda semestinya berada lebih lama di ruangan ini.
Dua kutipan milik Romo Mangun itu sekiranya membuat kita menjadi tahu bagaimana sikap sosial, politik, dan keagamaannya. Dapat kita rumuskan dalam satu kata: kemanusiaan. Sikap ini secara konsisten diartikulasikan Romo Mangun dalam berbagai media yang dekat dengan masyarakat. Setidaknya kita dapat melihatnya dalam beberapa bidang seperti agama, pendidikan, arsitektur, dan sastra.
 Bagi Romo Mangun, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk pembentukan identitas dan pendewasaan seseorang. Dengan demikian, pendidikan yang tidak memberikan kebebasan kepada murid dan hanya menyampaikan nilai-nilai mayoritas tidak akan menghasilkan “kemanusiaan”. Sebab, manusia merupakan animal rationale, makhluk yang memiliki berakal budi. Makhluk yang mampu berpikir, kemudian menentukan pilihan serta bertindakan atas dasar pilihannya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai manusia merdeka. Dan kemerdekaan ini mestinya telah dapat dicapai sejak masih kanak-kanak.
Bagi Romo Mangun, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk pembentukan identitas dan pendewasaan seseorang. Dengan demikian, pendidikan yang tidak memberikan kebebasan kepada murid dan hanya menyampaikan nilai-nilai mayoritas tidak akan menghasilkan “kemanusiaan”. Sebab, manusia merupakan animal rationale, makhluk yang memiliki berakal budi. Makhluk yang mampu berpikir, kemudian menentukan pilihan serta bertindakan atas dasar pilihannya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai manusia merdeka. Dan kemerdekaan ini mestinya telah dapat dicapai sejak masih kanak-kanak.
Setidaknya inilah yang dapat kita lihat melalui sekolah eksperimental Mangunan, dikhususkan tiga jenjang sekolah pertama, SD, SMP, SMA. Selain aturan pokok yang tidak memberatkan, nyaris kebijakan di sekolah ditentukan bersama antara pihak sekolah dengan wali murid. Misalnya besaran biaya sekolah, satu dengan lain murid bisa jadi berbeda, tergantung kemampuan masing-masing. Seragam hanya satu dan dipakai hari Senin, selebihnya pakaian asal sopan.
Pun demikian dengan metode pengajarannya. Sekolah ini menekankan kemampuan murid dalam mengeksplorasi pengetahuan sebagai ilmu kehidupan. Suasana pembelajaran diciptakan menyenangkan mungkin sehingga murid mudah menerima pengetahuan.
Pilihan model sekolah ini dapat kita lihat sebagai keberpihakan Romo Mangun kepada orang-orang miskin yang tak mampu menjangkau pendidikan. Juga pendidikan yang tak melakukan indoktrinasi kepada murid, melainkan “pemerdekaan”. Model pendidikan seperti ini bertahun-tahun kemudian menjadi model yang “mahal”.
 Jika sastra hanya selingan bagi Romo Mangun, tentu tak akan banyak karya yang dihasilkan. Setidaknya, ia telah menerbitkan 36 karya berupa esai, cerpen, dan novel. Karya masterpiece-nya, Burung-Burung Manyar diganjar Ramon Magsaysay Award pada 1996. Roman ini tidak sebagaimana umumnya roman masa revolusi yang menampilkan pahlawan dan musuh, melainkan menyoal bagaimana seorang manusia menjalani hidup dengan segala kompleksitasnya, dari mana mau ke mana atau sangkan paran.
Jika sastra hanya selingan bagi Romo Mangun, tentu tak akan banyak karya yang dihasilkan. Setidaknya, ia telah menerbitkan 36 karya berupa esai, cerpen, dan novel. Karya masterpiece-nya, Burung-Burung Manyar diganjar Ramon Magsaysay Award pada 1996. Roman ini tidak sebagaimana umumnya roman masa revolusi yang menampilkan pahlawan dan musuh, melainkan menyoal bagaimana seorang manusia menjalani hidup dengan segala kompleksitasnya, dari mana mau ke mana atau sangkan paran.
Dalam Burung-Burung Manyar, dengan jelas kelas-kelas sosial digambarkan melalui dua tokoh yang saling jatuh cinta tetapi beda pilihan hidup. Meski demikian, Romo Mangun tak menghadirkannya sebagai suatu pertentangan, melainkan bagian dari kompleksitas hidup dalam upaya mencari jati diri.
Pencitraan serupa dalam pula kita lihat dalam Burung-Burung Rantau yang berkisah tentang kelas menengah dan Balada Becak tentang kelas bawah yang miskin, tersisih, dan terpinggirkan.
Selain itu, kita juga perlu bertanya-tanya, mengapa Romo Mangun menovelkan Roro Mendut? Tokoh ini digunakan untuk menyatakan nalurinya yang membela pihak terjajah dan melawan dominasi laki-laki. Dalam triloginya, Roro Mendut, Genduk Duku, dan Lusi Lindri adalah tiga tokoh wanita yang memperjuangkan nasibnya sendiri yang menunjukkan keberpihakan Romo Mangun.
 Di dalam Ruang B, suguhan beberapa karya arsitektur Romo Mangun dibuat maketnya, yang kemudian dihubungkan dengan tema utama pameran Biennale Jogja XVI, Oseania. Tampak di satu dinding dua buku berjudul Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa dan Menuju Republik Indonesia Serikat karya Romo Mangun. Di dinding yang lain, beberapa kutipan Romo Mangun menjulur, salah duanya yang bisa dibaca di awal tulisan ini.
Di dalam Ruang B, suguhan beberapa karya arsitektur Romo Mangun dibuat maketnya, yang kemudian dihubungkan dengan tema utama pameran Biennale Jogja XVI, Oseania. Tampak di satu dinding dua buku berjudul Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa dan Menuju Republik Indonesia Serikat karya Romo Mangun. Di dinding yang lain, beberapa kutipan Romo Mangun menjulur, salah duanya yang bisa dibaca di awal tulisan ini.
Menyoal arsitektur, menurut Romo Mangun tidak ada yang persoalan yang gawat di dalamnya. Arsitek membuat penanda yang kemudian diwujudkan dalam bentuk petanda oleh tukang. Tetapi, di tangan Romo Mangun, arsitektur menemukan momentum dan pemaknaannya.
Satu kasus yang paling banyak jadi perbincangan adalah kompleks Kali Code yang berhasil diubah oleh Romo Mangun menjadi perkampungan yang menarik. Kompleks itu semula sebagai tempat pembuangan sampah. Rumah-rumah hanya terbuat dari kardus bekas, gedhek, dan sampah plastik. Pada 1984, Romo Mangun hadir menginisiasinya menjadi kompleks hunian yang layak.
Memilih Kali Code tentu bukan semata-mata karena lokasinya, melainkan orang-orang yang hidup di bantaran kali ini membutuhkan pendampingannya. Orang-orang yang tinggal adalah pengemis, pemulung, copet, hingga pekerja seks. Yang utama bagi Romo Mangun adalah mengubah stigma negatif. Melalui arsitektur, Kali Code menjadi kawasan bernapas kemanusiaan.
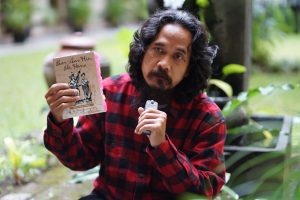 Sebagaimana diungkap di awal bahwa dua ruangan dedikasi untuk Romo Mangun, terlalu kecil untuk menampung kebesarannya, jika tidak dirasakan betul imaji-imaji pengetahuan yang dibangun dalam ruang itu. Tak cukup dengan itu, kurator pameran tersebut, Ayos Purwoaji juga menyelenggarakan Sinau Romo Mangun melalui buku Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa.
Sebagaimana diungkap di awal bahwa dua ruangan dedikasi untuk Romo Mangun, terlalu kecil untuk menampung kebesarannya, jika tidak dirasakan betul imaji-imaji pengetahuan yang dibangun dalam ruang itu. Tak cukup dengan itu, kurator pameran tersebut, Ayos Purwoaji juga menyelenggarakan Sinau Romo Mangun melalui buku Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa.
Buku itu menjadi kurikulum utama dalam setiap kelas yang diselenggarakan seminggu sekali. Tak sendirian, Biennale Jogja XVI bekerja sama dengan Laboratorium Sejarah, Teori, Kajian Teknologi dan Desain FAD UKDW (Yogya), Bilik Literasi (Colomadu), Penerbit Hatopma (Kab. Bengkulu Utara), Yayasan Dinamika Edukasi Dasar (Yogya), dan Pusat Dokumentasi Arsitektur (Jakarta).
Terdapat 24 peserta kelas yang secara intens membaca Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa dan kemudian menuliskan pandangannya terkait buku tersebut. Beberapa contoh topik yang muncul seperti agama, anak, senjata, gaya hidup, dan lain sebagainya. Tulisan peserta akan dibukukan dan diluncurkan pada akhir penyelenggaraan Biennale Jogja XVI.Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa sendiri merupakan novel berlatar sejarah abad ke-16-17 yang membentangkan kebudayaan masyarakat Halmahera, Maluku Utara, dengan Suku Tobelo. Tampak dalam novel ini, Romo Mangun berpihak pada kaum terjajah atas kesewenangan praktik oleh bangsa Portugal, Spanyol, dan Belanda.